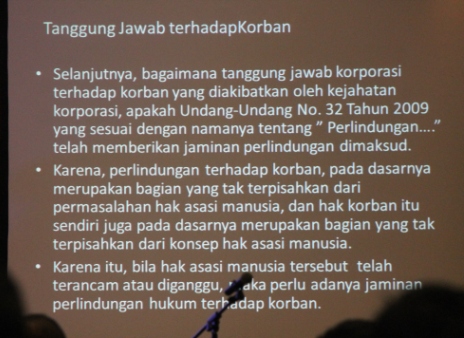Potensi kehilangan bisnis itu datang dari Jan van Dijk, Principal Officer of the United Nations Center for International Crime Prevention. Omongan van Dijk disitir kembali Harkristuti Harkrisnowo di depan sejumlah petinggi LPSK dan tamu undangan di Jakarta, Kamis (08/9) lalu. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia berbicara tentang perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana.
Para korban kejahatan (victims of crime) banyak yang tidak puas terhadap layanan dalam sistem peradilan pidana. Padahal korban dan saksi memegang posisi kunci untuk memproses tersangka atau terdakwa lebih lanjut. Ironisnya, korban atau saksi tak selalu memperoleh perlakuan yang menunjukkan penghargaan terhadap keterangan yang diberikannya.
Salah satu yang acap terjadi di pengadilan Indonesia adalah menunggu lama. Korban atau saksi menunggu berjam-jam sebelum akhirnya diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangan. Sistem peradilan pidana cenderung lebih menaruh perhatian kepada tersangka/terdakwa. Akibatnya, hak-hak korban atau saksi sering terabaikan. (Baca juga: Restorative Justice Sebagai Viktimologi Postmodern).
Harkristuti mengingatkan korban juga perlu mendapatkan pengakuan secara adekuat dan diperlakukan sesuai harkat dan martabat manusia. Korban berhak mengakses mekanisme yuridis dan penanganan segera akan kerugian yang dialaminya. Prinsip-prinsip ini jelas diatur dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. Hak-hak korban juga diatur jelas dalam 1985 UN Victims’ Declaration. Perundang-undangan Indonesia pun sudah banyak mengaturnya.
Ironisnya, korban yang sudah memperjuangkan hak hukumnya melalui mekanisme legal pun masih harus menunggu bertahun-tahun. Menang di pengadilan bukan jaminan hak korban dipenuhi sesegera mungkin. Nasib nahas semacam inilah yang sedang dialami korban tindakan oknum kepolisian di Sumatera Barat. Menang atas tuntutan ganti rugi melawan institusi negara di pengadilan tak menjamin hak mereka langsung dibayarkan.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Charles Simabura, menilai sikap enggan membayar hak korban yang sudah diputuskan pengadilan sebagai preseden buruk penegakan hukum. Jika nanti benar-benar tak dibayarkan kepada korban, sama saja itu bentuk pelanggaran hukum. “Preseden ini jika dibiarkan mungkin saja akan diikuti oleh lembaga lain, dan jelas akan meruntuhkan wibawa hukum pada umumnya, dan dunia peradilan pada khususnya,” jelas Charles kepada Hukumonline.
Kekecewaan terhadap layanan sistem peradilan pidana bukan kali ini saja terjadi. Dalam kasus tindak pidana terorisme, nasib korban juga sering terabaikan. Stigma teroris terkesan langsung melekat kepada seseorang begitu pasukan Densus 88 Mabes Polri melakukan penangkapan. Orang yang sudah terkena stigma itu bisa diperlakukan sewenang-wenang seperti yang pernah menimpa Sriyono.
Ketua Pansus RUU Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 (R. Muhammad Syafi’i, mengakui korban tindak pidana terorisme masih mengeluhkan pelayanan yang diberikan. Sesuai mandate UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, para korban berhak atas bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta kompensasi. Syafi’i mengakui dalam praktik, pelayanan terhadap korban masih harus diperbaiki. “Masih perlu perbaikan,” ujarnya.
Sebagian korban atau saksi mencari rumah perlindungan agar mereka relatif aman dari ancaman siapapun, baik dari tersangka/terdakwa maupun pihak ketiga. Dalam konteks ini, ada tren positif. Setidaknya, positif dalam arti keinginan meminta perlindungan ke LPSK kian bertambah. Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, menyebutkan tahun ini (hingga Juli) ada 1.140 permohonan yang masuk. Jumlah ini hampir mendekati total permohonan perlindungan yang masuk tahun 2015,yakni 1.687 permohonan.
| Tahun | Jumlah permohonan |
| 2009 | 94 |
| 2010 | 154 |
| 2011 | 340 |
| 2012 | 655 |
| 2013 | 1.560 |
| 2014 | 1.076 |
| 2015 | 1.687 |
| 2016 (Januari-Juli) | 1.140 |
Persoalannya, LPSK bukan satu-satunya lembaga yang bersinggungan dalam sistem peradilan pidana. Kepolisian dan Kejaksaan memegang peranan yang sangat penting, dan berpengaruh pada tingkat kepercayaan publik sebagai ‘pelanggan’.
Masalahnya bukan pada regulasi. Indonesia sudah punya sederet peraturan mengenai perlindungan korban atau saksi. Bahkan RUU KUHP, kata Prof. Harkristuti Harkrisnowo, sudah memuat sejumlah aturan yag ‘melindungi’ korban atau saksi. Misalnya Pasal 340 RUU KUHP yang mengancam pidana siapapun yang melakukan penyerangan secara langsung kepada saksi saat memberikan kesaksiannya, yang mengakibatkan tidak dapat memberikan kesaksian.
Masalahnya lebih pada implementasi peraturan perundang-undangan yang ada. Justru potensi bankrut lembaga-lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, seperti disebut Jan van Dijk, timbul karena layanan yang kurang memuaskan korban kejahatan.