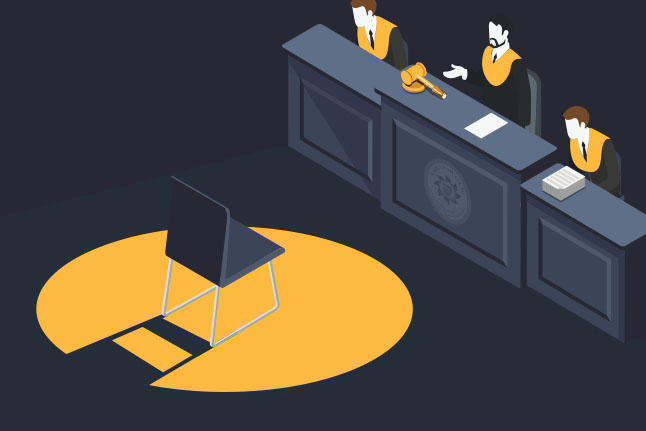Salah satu yang diatur dalam Perma adanya empat larangan bagi hakim saat memeriksa perempuan yang berharapan dengan hukum. Pertama, hakim tidak boleh menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan yang berhadapan dengan hukum.
Kedua, hakim tidak boleh membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender. (Baca: Penting!!! Urgensi PERMA Pedoman Mengadili Perkara Perempuan)
Ketiga, hakim tidak boleh mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku. Keempat, hakim dilarang mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.
Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Sedangkan yang dimaksud stereotip gender adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki.
Sementara untuk diskriminasi terhadap perempuan dalam Perma yang disebutkan merupakan segala pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
Ketua Harian MaPPI FHUI, Choky Risda Ramadhan mengatakan, sepanjang 2015-2016, MaPPI FHUI berkolaborasi dengan LBH Apik Jakarta melakukan penelitian penanganan perkara pidana perempuan melalui ratusan putusan pengadilan, wawancara hingga focus group discussion (FGD).
Hasilnya, ditemukan adanya ketidakadilan dalam penanganan perkara terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Ketidakadilan tersebut mulai dari stereotip gender hingga perlakuan diskriminatif. Menurut Choky, serangkaian ketidakadilan tersebut berdampak pada penanganan perkara di pengadilan menjadi kurang optimal dalam memberikan perlindungan dan keadilan.
“Seperti korban perkosaan seringkali diperiksa oleh hakim dan penegak hukum lain mengenai riwayat seksual (masih perawan atau tidak), pakaian apa yang dikenakan, gaya apa yang dilakukan pelaku dsb,” katanya kepada Hukumonline melalui pesan elektronik, Rabu (9/8).
Dari dokumen yang dirilis MaPPI berjudul “Kekerasan Seksual di Indonesia: Data, Fakta & Realita” terungkap bahwa jumlah kekerasan seksual tahun 2012-2015 mengalami pasang surut. Data ini diperoleh MaPPI dari Komnas Perempuan. Dalam dokumen itu disebutkan setidaknya terdapat 15 bentuk kekerasan seksual.
(Baca: Lima Belas Bentuk Kekerasan Seksual)
Mulai dari perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penghukuman bernuansa seksual, perbudakan seksual, prostitusi paksa, pemaksaan penghamilan, perdagangan perempuan, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi, intimidasi seksual, pemaksaan aborsi, praktik tradisi (misal sunat perempuan) dan kontrol seksual.
Sejumlah bentuk kekerasan seksual tersebut berdampak buruk bagi korban. Mulai dari trauma secara seksual, luka secara fisik, kehamilan tidak diinginkan, perilaku cenderung berubah, penyakit menular seksual, dalam beberapa kasus adanya dorongan untuk bunuh diri, dampak psikologis, stigma dari masyarakat hingga gangguan fungsi reproduksi.

Dilansir dari dokumen MaPPI berjudul “Kekerasan Seksual di Indonesia: Data, Fakta & Realita”
Sebuah Terobosan
Apresiasi atas terbitnya Perma ini datang dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi Widodo mengatakan, pembentukan Perma ini merupakan sebuah terobosan. Materi-materi yang diatur di Perma ini belum pernah terakomodir dalam peraturan perundang-undangan, khususnya KUHAP.
Menurut Supriyadi, meski Perma ini secara lebih luas mengatur pedoman hakim dalam mengadili perkara, baik pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan, namun keberadaannya sangat diperlukan terutama dalam peradilan pidana dan perempuan yang berhadapan dengan hukum.
Pada praktiknya, lanjut Supriyadi, sebelum Perma ini terbit terdapat inkonsistensi persepsi hakim terkait dengan proses peradilan yang melibatkan perempuan. Bahkan, terdapat beberapa putusan hakim yang memberikan pertimbangan-pertimbangan justru menjauhkan perempuan untuk mendapatkan akses keadilan.
“Sebagai contoh, dalam perkara kasus pencabulan dengan nomor perkara 1391/Pib.B/PA/2007/PN.LP, hakim justru memberikan pertimbangan yang tidak relevan dengan menjabarkan perbuatan-perbuatan korban yang dinilainya melanggar ketertiban umum, seperti riwayat seksual korban, hal ini justru membuat korban semakin sulit memperoleh keadilan,” tulis Supriyadi dalam siaran persnya yang diterima Hukumonline.
(Baca: Aturan Perkosaan dalam Revisi KUHP Dinilai Sempit)
Selain itu, lanjut Supriyadi, Perma ini juga dapat dijadikan sebagai momentum baik bagi lahirnya putusan-putusan yang progresif dalam mengakomodir hak-hak korban khususnya perempuan. Bahkan, Perma ini diharapkan dapat mengantisipasi penafsiran rumusan-rumusan tindak pidana yang justru merugikan korban.
“Seperti yang diatur dalam Pasal 5 PERMA dimana hakim dilarang untuk menujukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi ataupun membenarkan terjadinya diskriminasi gender termasuk di dalamnya mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan pengalaman atau latar belakang seksual soal korban,” tutupnya.