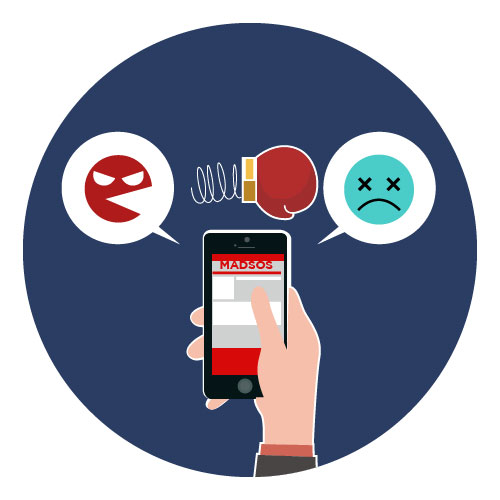Setidaknya, dalam pandangan Deputi Direktur Elsam, Wahyudi Djafar, revisi UU ITE yang digagas Pemerintah belum mampu menyelesaikan persoalan utama yang selama ini muncul. Pengujian UU ITE ke Mahkamah Konstitusi, plus banyaknya ‘korban’ implementasi Undang-Undang ini, menunjukkan ada persoalan serius.
Menurut Wahyudi, ada empat hal penting yang masih perlu diperdebatkan. Pertama, RUU itu masih mencantumkan pasal-pasal pidana konvensional yang selama ini dianggap pasal karet yaitu Pasal 27, 28 dan 29 UU ITE. Faktanya, pasal-pasal ini, khususnya norma Pasal 27 ayat (3) UU ITE, memuat ancaman ancaman serius terhadap kebebasan berekspresi. Menurut dia, ketentuan pidana sejenis itu cukup diatur KUHP. “Ketentuan itu harus dikembalikan sepenuhnya ke KUHP,” katanya di Jakarta, Rabu (08/6).
Kedua, RUU Perubahan UU ITE menurunkan sanksi pidana dari 6 tahun jadi 4 tahun. Menurut Wahyudi ancaman itu masih lebih besar dibandingkan KUHP. Ia meyakini hal itu tidak akan menyurutkan pelaporan terhadap orang yang menggunakan hak berekspresinya secara sah melalui medium internet. Faktanya, ketentuan itu banyak digunakan kelompok yang punya kekuatan secara politik dan ekonomi.
Ketiga, soal penyadapan, RUU Perubahan UU ITE mengamanatkan pemerintah untuk menerbitkan peraturan teknis, seolah itu sesuai putusan MK No. 5/PUU-VIII/2010. Padahal dalam putusan itu MK mengamanatkan Pemerintah dan DPR mengatur secara ketat dan komprehensif praktik-praktik penyadapan melalui UU Penyadapan.
Keempat, prosedur pemblokiran konten internet. Wahyudi melihat dalam RUU Perubahan UU ITE belum mengatur prosedur pemblokiran padahal mestinya prosedur pemblokiran menjadi satu bagian integral dalam prinsip tata kelola internet. Selama ini belum ada regulasi yang mengatur khusus mekanisme pemblokiran konten internet.
Beberapa regulasi yang menyinggung soal pemblokiran konten internet hanya UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Itu pun pengaturannya terbatas, UU Pornografi hanya memberi kewenangan pemerintah untuk memblokir konten internet yang berisi pornografi dan terkait pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur UU Hak Cipta.
Wahyudi berpendapat pembatasan hak untuk memperoleh informasi lewat internet harusnya diatur jelas dan mengacu HAM. Selama ini pemerintah memberi ruang besar terhadap penyedia jasa internet (ISP) untuk melakukan blokir terhadap konten internet, seperti diatur dalam Permenkominfo No. 19 Tahun 2004 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.
Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2012-2015, Semuel A Pangerapan, menyarankan Pemerintah dan DPR untuk mencabut Pasal 27, 28 dan 29 UU ITE. Energi legislator banyak dihabiskan membahas dan memperdebatkan ketiga pasal itu, sehingga sejumlah norma lain yang kurang mendapat perhatian. Misalnya, mengatur lebih jelas agar data dan informasi yang diperoleh dari internet bisa disebut otentik, dan masalah tandatangan digital. “Sebagian pasal yang bermanfaat bagi masyarakat harus diatur agar implementatif,” ujar Semuel.
Sebagai pelaku usaha yang bergerak dibidang ISP, Semuel, menilai tidak tepat jika ISP diberi kewenangan untuk memblokir konten internet. ISP hanya berwenang pada tataran teknis. Kewenangan itu sebaiknya tetap ada di tangan Pemerintah. Dengan kewenangan itu, Pemerintah mengatur konten apa saja yang tidak layak untuk ditampilkan di internet.
Semuel khawatir jika kewenangan pemblokiran dimiliki ISP akan berdampak pada penegakan hukum dalam dunia digital. Bisa saja aparat penegak hukum kesulitan ketika mencari pembuktian digital untuk mengungkap sebuah kasus. Dalam kasus cybercrime, pembuktian digital sangat penting karena itu yang paling otentik. “Kaidah internet itu tidak boleh dilanggar, internet harus netral,” paparnya.